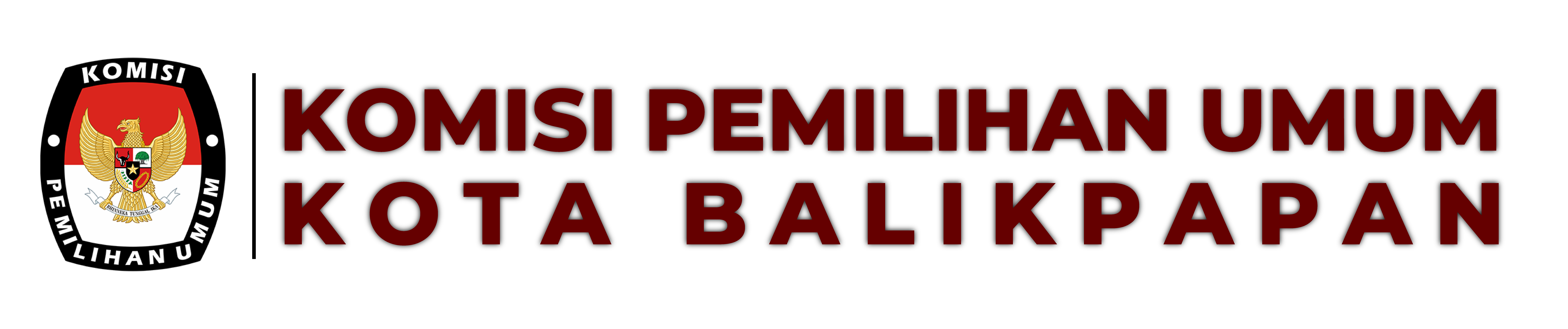Kartini, Perempuan, dan Demokrasi: Dari Emansipasi Menuju Kepemimpinan Publik
Rasanya mafhum bagi bangsa Indonesia setiap 21 April merupakan hari Kartini. Sebagai bentuk mengenang salah satu sosok wantia yang memperjuangkan hak perempuan. Ia tidak hanya seorang perempuan yang menulis surat-surat panjang penuh gelora pikir, tetapi juga penanda zaman—sebuah simbol tentang bagaimana suara perempuan tak selayaknya dibungkam oleh batas dan kebiasaan.
Bagi saya, mengenang Kartini bukan perkara seremonial. Ini adalah soal refleksi. Utamanya sebagai bagian dari penyelenggara demokrasi di tingkat lokal. Dalam kerja-kerja kepemiluan, saya menyaksikan langsung bagaimana ruang-ruang publik masih belum sepenuhnya ramah bagi perempuan, meski berbagai regulasi telah memberi jalan. Representasi politik perempuan sering kali masih menjadi angka statistik yang dikejar, bukan kesadaran yang sungguh-sungguh dihidupi.
Padahal, demokrasi yang sehat harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Perempuan bukan hanya pemilih, mereka adalah pembentuk arah. Dalam setiap rumah, dalam komunitas, dan mestinya—dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik.
Saya teringat bagaimana tulisan korespondensi Kartini kepada kurang lebih 106 sahabat penanya. Di kemudian hari disusun oleh salah satu sahabat penanya, Jascque Abendanon. Dikenal dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Bahwa Kartini menulis tentang “gelap pekat” kehidupan kaum perempuan yang perlahan-lahan harus dilawan dengan cahaya ilmu, pendidikan, dan keberanian. Emansipasi, bagi Kartini, bukan tentang menyerupai laki-laki, tetapi tentang menyadari potensi dirinya sebagai manusia yang utuh, bebas, dan merdeka.
Kini, lebih dari seabad setelah Kartini berpulang, kita masih menghadapi tantangan yang tak sederhana. Perempuan yang hendak tampil sebagai pemimpin sering harus melipatgandakan usahanya. Ia harus tampil cakap, tangguh, dan tetap dianggap “diterima” dalam konstruksi sosial yang masih bias. Tidak sedikit pula yang tersandera oleh beban ganda—antara harapan publik dan urusan domestik yang belum terbagi adil.
Namun harapan haruslah tetap tumbuh dan dikawal. Di Balikpapan, saya melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam kerja-kerja pemilu—sebagai penyelenggara, pengawas, relawan, hingga penggerak komunitas. Mereka hadir dengan dedikasi, integritas, dan kepekaan yang menjadi nilai tambah bagi demokrasi kita.
Beberapa dari mereka bahkan menjadi pemimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam struktur adhoc penyelenggara pemilu. Ada yang memimpin logistik, mengelola perencanaan, hingga menjadi juru bicara yang mampu menjembatani pemilih dengan informasi yang mencerahkan. Mereka tidak hanya bekerja dengan sistem, tetapi dengan hati.
Kita juga tidak boleh melupakan tokoh-tokoh perempuan di Kalimantan Timur yang selama ini menjadi pionir dalam pembangunan sosial dan politik. Baik di DPRD, dalam organisasi masyarakat, maupun sebagai tokoh adat dan budaya. Keteladanan mereka membuktikan bahwa kepemimpinan tidak mengenal jenis kelamin—ia adalah soal visi dan keberanian mengambil tanggung jawab.
Tugas kita bersama hari ini adalah merawat ruang ini. Membuka kesempatan lebih luas, mendorong afirmasi yang sehat, dan mendidik publik untuk menilai kepemimpinan bukan dari jenis kelamin, melainkan dari kapasitas, rekam jejak, dan komitmen.
Sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, saya meyakini bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan adalah bagian dari ajaran luhur yang diwariskan para guru kami. Dan Kartini, dalam versinya sendiri, telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu bisa diperjuangkan lewat tulisan, keberanian, dan ketulusan.
Kartini mengawali perjuangan ini dengan pena. Kini, sepatutnya kita melanjutkannya dengan kebijakan, kebudayaan, dan keberanian untuk mengubah cara pandang. Sebab demokrasi sejati bukan hanya tentang suara yang dihitung, tapi tentang siapa yang benar-benar diberi ruang untuk bersuara.
Prakoso Yudho Lelono
![]()
![]()
![]()