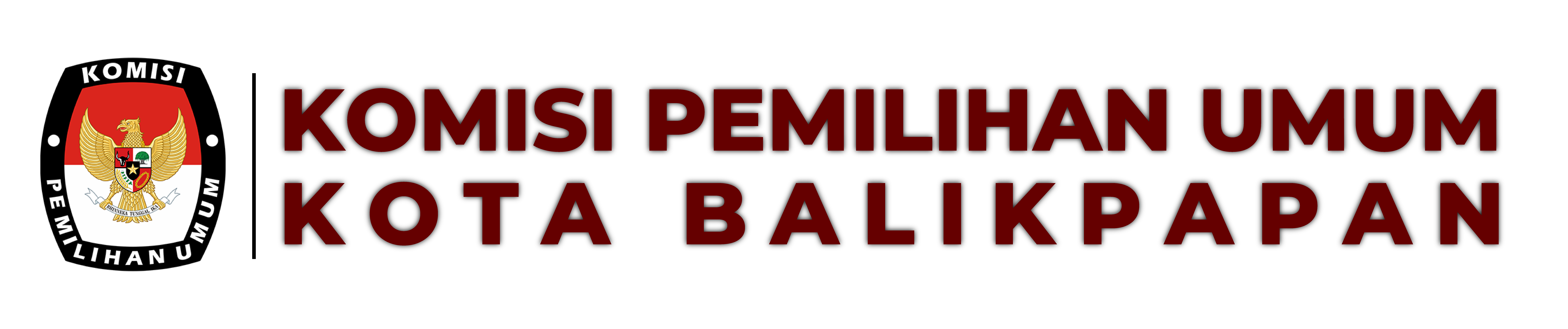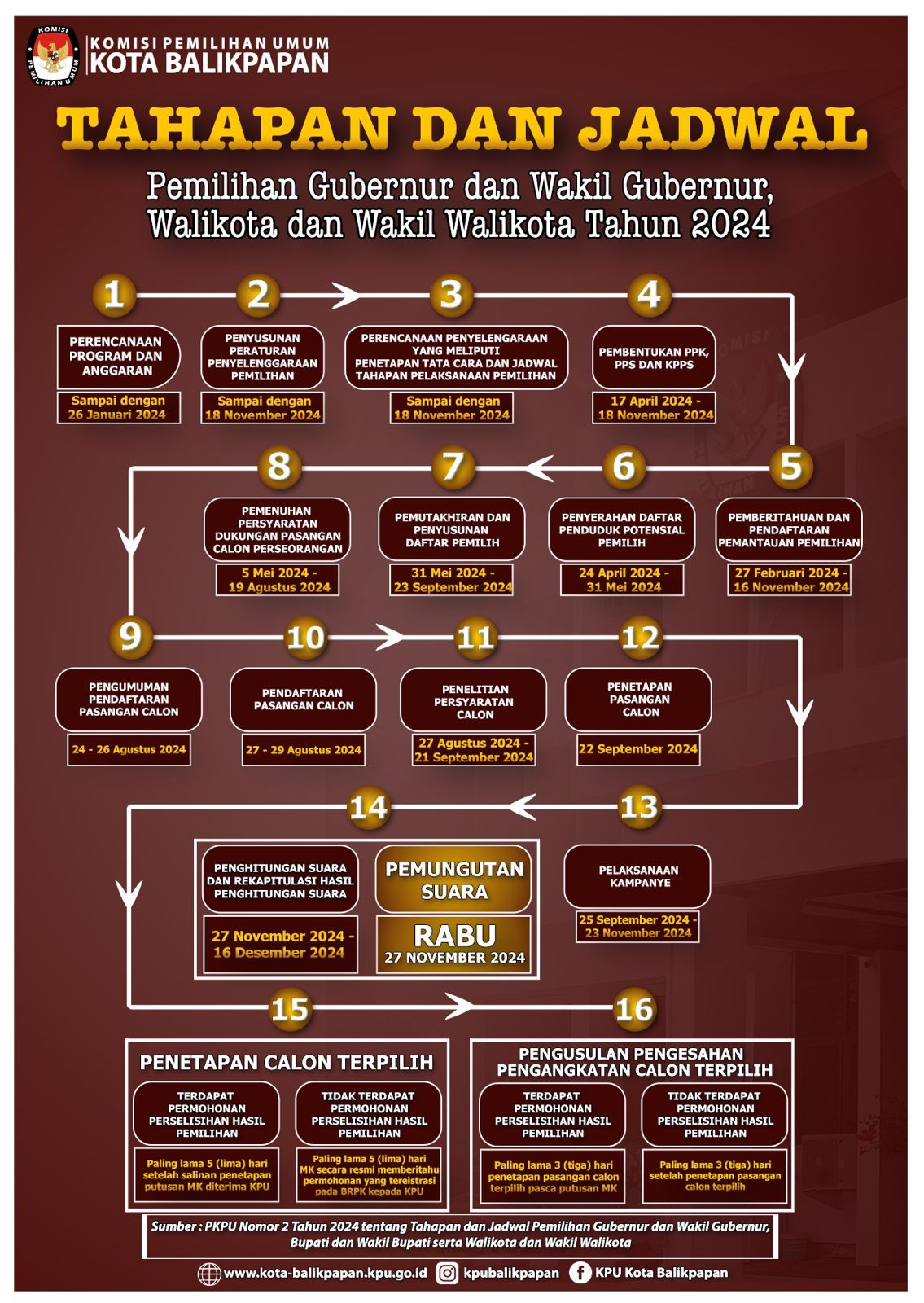Penyerahan Dokumen Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kke DPRD Kota Balikpapan
Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono beserta Anggota KPU Kota Balikpapan Farida Asmauanna, Muhammad Rizal, Makta, dan Suhardy menyerahkan Dokumen Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Rahmad Mas’ud S.E., M.E. dan Dr. Ir. Bagus Susetyo M.M. kepada DPRD Kota Balikpapan di Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Hari Jumat, 10 Januari 2025. Dokumen diterima oleh Bagian Persidangan, Ibu Mayang I.R Biru. #KPUMelayani #Pilkadaserentak2024 ....

KPU Kota Balikpapan Tetapkan 541.411 Pemilih: Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV 2025 Sinyal Peningkatan Akurasi Data
Kota Balikpapan, 8 Desember 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Bertempat di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan, kegiatan ini menegaskan komitmen KPU dalam menjalankan amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2025 untuk menjaga integritas data pemilih. Pleno terbuka ini menjadi wujud transparansi, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan utama di Kota Balikpapan, termasuk: Kepolisian Resor Kota Balikpapan Komando Distrik Militer 0905 Kota Balikpapan Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Balikpapan Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Dhomber Kota Balikpapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Dalam kesempatan ini, KPU Kota Balikpapan secara resmi menetapkan jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 541.411 pemilih. Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial, naik dari 536.514 pemilih pada Triwulan III 2025. Peningkatan ini membuktikan efektivitas proses pemutakhiran data yang dilakukan secara kolaboratif. Melalui rapat pleno ini, KPU Kota Balikpapan menjamin bahwa akurasi, validitas, dan transparansi data pemilih akan selalu menjadi landasan utama demi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. ....

KPU Kota Balikpapan Tuntaskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, Jaga Akurasi Daftar Pemilih
Kota Balikpapan, 4 Desember 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sukses melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Pertemuan penting ini diselenggarakan di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan dan menandai triwulan terakhir pemutakhiran data di tahun ini. Dalam rakor tersebut, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Balikpapan, Bapak Makta, memaparkan secara rinci mengenai progres PDPB yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak Triwulan II hingga Triwulan IV tahun 2025. Presentasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh data pemilih di Kota Balikpapan tetap valid dan up-to-date. Acara ini semakin berbobot dengan kehadiran BAWASLU Kota Balikpapan, yang turut memberikan masukan kritis, termasuk melakukan sampling nama untuk memverifikasi dan memastikan pemilih telah terakomodasi dengan benar dalam proses pemutakhiran. KPU Kota Balikpapan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas data dengan mengundang berbagai instansi strategis, antara lain: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud), serta Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Balikpapan. Sinergi antarlembaga ini menjadi kunci utama untuk menjamin data pemilih mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk warga binaan dan personel institusi vertikal di Kota Balikpapan, sehingga hak konstitusional setiap warga negara dapat terpenuhi. ....

KPU Kota Balikpapan Sosialisasi PKPU No. 3 Tahun 2025: Dorong Partai Politik Pahami Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan
Dalam rangka memastikan pemahaman yang seragam mengenai regulasi kepemiluan terkini di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2025. PKPU ini mengatur tentang mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan penting ini dilaksanakan di aula KPU Kota Balikpapan pada hari Senin, 1 Desember 2025. Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder kunci, termasuk perwakilan dari DPRD Kota Balikpapan, Kabag Pemerintahan Kota Balikpapan, dan Kesbangpol Kota Balikpapan, serta perwakilan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dan awak media. Untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi tersebut, KPU Kota Balikpapan menghadirkan Abdul Qayyim Rasyid, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan pemaparan komprehensif secara daring mengenai dasar hukum regulasi serta mekanisme rinci pelaksanaan PAW. Sosialisasi PKPU No. 3 Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang akurat kepada seluruh partai politik dalam melaksanakan proses PAW, menjamin proses transisi keanggotaan dewan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. ....

Sinergi Pemkot, ANRI, dan KPU Kota Balikpapan Kuatkan Penyelamatan Arsip Statis sebagai Aset Sejarah Daerah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam tata kelola administrasi kelembagaan yang profesional dengan memenuhi undangan penting dari Pemerintah Kota Balikpapan. Ketua KPU Kota Balikpapan turut serta dalam Workshop Pengelolaan dan Penyusunan Arsip Statis yang diselenggarakan di Hotel Gran Senyiur Kota Balikpapan. Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya penyelamatan arsip yang memiliki nilai sejarah tinggi dan berfungsi sebagai Memori Kolektif Kota Balikpapan. Kehadiran arsip yang tersusun baik sangat vital untuk menjaga akuntabilitas dan jejak rekam sejarah pembangunan kota. Workshop ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Kota Balikpapan serta dari lembaga kearsipan tertinggi negara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Acara ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, terlihat dari daftar tamu undangan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan BUMD Kota Balikpapan, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, hingga Stakeholder Kota Balikpapan terkait lainnya, menegaskan pentingnya penyelamatan arsip bagi seluruh elemen daerah. ....

Demi Pemilu Inklusif: KPU Kota Balikpapan Audiensi ke PPDI Kota Balikpapan, Rencanakan Program Sosialisasi Khusus Disabilitas
Dalam upaya memastikan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan audiensi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI Kota Balikpapan). Kunjungan koordinasi ini berlangsung pada hari Selasa, 18 November 2025. Kunjungan KPU Kota Balikpapan diwakili oleh Suhardy, Anggota KPU Kota Balikpapan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM). Dalam pertemuan tersebut, Suhardy menyampaikan rencana KPU untuk mengadakan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih yang secara spesifik ditujukan bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan. Rencana kegiatan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh perwakilan DPC PPDI Kota Balikpapan. Mereka menyatakan, “merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi teman-teman disabilitas terlibat dalam proses peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilu yang akan datang,” menunjukkan kesiapan mereka untuk berkolaborasi. Kegiatan audiensi ini juga dihadiri oleh Kasubbag Parhubmas dan SDM KPU Kota Balikpapan serta staf Sekretariat KPU Kota Balikpapan, menandai keseriusan lembaga dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. ....

Publikasi
Opini

*Oleh: Prakoso Yudho Lelono Setiap 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Namun, pertanyaan yang layak diajukan: apakah kesaktian itu masih hidup dalam keseharian generasi muda, atau sekadar menjadi ritual tahunan yang diwarnai upacara dan hafalan sila? Di tengah hiruk-pikuk politik identitas dan derasnya arus informasi di media sosial, Pancasila seakan hadir sebagai slogan yang dikutip, tetapi tidak sungguh-sungguh dipraktikkan. Ironisnya, kelompok yang seharusnya menjadi motor penggerak aktualisasi nilai Pancasila—yakni generasi muda—kadang justru terjebak dalam polarisasi dan konten-konten dangkal yang berjarak dari semangat persatuan dan keadilan sosial. Generasi muda sering digambarkan sebagai pewaris masa depan bangsa, agen perubahan, dan pilar utama demokrasi. Namun, seberapa jauh mereka benar-benar memahami Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai teks hafalan. Tetapi sebagai etika hidup yang membimbing sikap. Hal ini semakin relevan ketika kita menyaksikan betapa cepatnya informasi (baik yang mencerahkan maupun yang menyesatkan) menyebar melalui media sosial, ruang yang paling dekat dengan kehidupan anak muda hari ini. Tidak bisa dipungkiri, banyak anak muda mampu menyebutkan lima sila Pancasila dengan fasih, tetapi hanya sedikit yang berusaha menggali makna filosofis dan implikasi sosial dari sila-sila itu. Ketika Sila Ketiga berbunyi “Persatuan Indonesia”, apakah hal itu hanya sebatas barisan kata, atau benar-benar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, seperti menolak dan menahan diri turut serta akan ujaran kebencian. Menahan diri dari penyebaran berita hoaks, atau membangun ruang diskusi yang sehat di komunitas dan media sosial? Sayangnya, polarisasi politik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian generasi muda lebih mudah terbawa arus kontestasi yang sempit daripada memegang teguh nilai persatuan. Media sosial kerap menjadi panggung pertempuran opini yang penuh caci maki, alih-alih menjadi wadah dialog konstruktif. Sila Keempat tentang musyawarah mufakat seakan hilang dalam derasnya debat kusir. Sementara Sila Kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sering kali dikalahkan oleh ujaran kasar yang viral. Di sinilah tantangan nyata aktualisasi Pancasila: bagaimana nilai-nilai luhur tidak berhenti pada upacara, simbol, atau hafalan, melainkan masuk ke ruang digital yang setiap hari memengaruhi pikiran dan sikap generasi muda. Namun, ditengah kondisi seperti ini, kita tak patut untuk hanya bermuram durja dan berhenti pada sikap pesimistis. Banyak juga contoh anak muda yang berusaha menghidupkan Pancasila dalam aksi nyata. Komunitas literasi yang membuka ruang baca gratis di kampung-kampung, gerakan lingkungan yang memperjuangkan kelestarian alam, hingga inisiatif kreatif di media sosial yang menyebarkan konten edukatif dan toleran. Semua itu adalah bukti bahwa nilai-nilai Pancasila bisa aktual dan relevan, bahkan di era digital. Mereka membuktikan bahwa menjadi “pancasialis” bukan berarti mengulang jargon, melainkan mengintegrasikan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial ke dalam tindakan sehari-hari. Dalam konteks komunitas, generasi muda punya peran besar sebagai penggerak. Misalnya, kegiatan bakti sosial, gerakan berbagi makanan bagi kaum dhuafa, atau program diskusi lintas agama yang digagas di banyak kota besar. Aktivitas sederhana ini adalah wujud nyata sila-sila Pancasila: kepedulian pada sesama, penguatan solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jika nilai ini dipelihara sejak dini, generasi muda tidak hanya menghafal sila, melainkan merasakan makna hidup bersama dalam keberagaman. Sementara di media sosial, tantangannya lebih berat. Dunia digital memang rawan dipenuhi dengan narasi kebencian, hoaks, dan ujaran provokatif. Namun, justru di ruang ini generasi muda bisa membuktikan bahwa mereka mampu mengaktualisasikan Pancasila. Dengan membangun konten yang mengedepankan toleransi, memviralkan aksi positif, atau menyuarakan kritik yang santun dan berbasis data. Anak muda bisa menjadikan media sosial sebagai “laboratorium Pancasila.” Keberanian untuk melawan arus negatif dengan kreativitas positif adalah bentuk kesaktian baru Pancasila di abad ke-21 ini. Momentum Hari Kesaktian Pancasila tahun ini seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi ruang refleksi mendalam, khususnya bagi generasi muda. Apakah kita akan puas menjadi generasi penghafal sila, atau kita berani dan mampu menjadi generasi penggerak yang menjadikan Pancasila sebagai napas perjuangan di tengah tantangan zaman? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan ajakan untuk melihat diri sendiri: sudahkah kita benar-benar menghadirkan nilai Pancasila dalam sikap, ucapan, dan tindakan? Pancasila tidak menuntut kita menghafalnya dengan mulut yang fasih. Tetapi menagih konsistensi pada tindakan yang membela kemanusiaan, merawat persatuan, menghidupkan musyawarah, dan memperjuangkan keadilan. Media sosial, komunitas, maupun ruang publik lainnya harus dijadikan laboratorium aktualisasi nilai-nilai tersebut. Jika generasi muda berani mengambil peran ini, maka Pancasila tidak hanya sakti karena pernah menyelamatkan bangsa di masa lalu, melainkan juga akan terus hidup, bekerja, dan menyelamatkan bangsa di masa depan. *Ketua KPU Kota Balikpapan

Oleh: Prakoso Yudho L. *Ketua KPU Kota Balikpapan, pemerhati sosial-politik dan penggerak literasi demokrasi. Hari ini, Jumat, 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H. Tahun Baru Islam. Semalam tidak tampak kegiatan dan acara acara dengan euphoria. Tidak ada pesta kembang api atau panggung hiburan besar-besaran. Suasana teduh, penuh makna, dan sarat renungan. Bagi umat Islam, 1 Muharram bukan sekadar pergantian kalender, tapi momentum spiritual yang kuat: peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebuah perjalanan monumental yang bukan hanya berpindah tempat, tapi juga perubahan arah, nilai, dan peradaban. Dalam konteks Indonesia hari ini, apalagi menjelang Pilkada di berbagai daerah, semangat hijrah sepatutnya tidak hanya diperingati, tapi juga dihayati. Terutama oleh mereka yang mengemban atau berambisi untuk mengemban amanah kepemimpinan. Hijrah hari ini bukan lagi tentang langkah kaki menuju kota baru, melainkan langkah hati dan pikiran menuju moralitas yang lebih luhur dalam berpolitik dan memimpin. Belajar dari Hijrah Nabi Mari kita mundur sejenak ke lebih dari 1400 tahun lalu. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, mereka tidak hanya mencari perlindungan, tapi membawa misi peradaban: membangun masyarakat baru yang adil, terbuka, dan beradab. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai nabi dan utusan Tuhan, tapi juga sebagai pemimpin politik, kepala negara, sekaligus pemersatu suku dan golongan yang sebelumnya saling bermusuhan. Dari hijrah inilah lahir konstitusi pertama dalam sejarah Islam yaitu Piagam Madinah. Dimana ada komitmen menjamin kebebasan beragama, kesetaraan hak, dan keadilan sosial. Ini bukan dongeng belaka. Ini adalah realitas sejarah yang membuktikan bahwa moralitas dan spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan dan politik. Sekarang mari kita tengok kehidupan kita saat ini. Apa yang kita lihat di panggung politik hari ini? Sayangnya, politik masih sering dipersepsikan sebagai ruang adu siasat an sich. Saling jegal, bahkan saling intrik licik yang jauh dari nilai-nilai moral. Bukan rahasia lagi bahwa politik di negeri ini kerap disandera oleh pragmatisme dan kepentingan jangka pendek. Ada yang rela mengorbankan idealisme demi kursi kekuasaan. Ada juga yang menjadikan politik sebagai kendaraan pribadi, bukan amanah public, dan celakanya hanya untuk kepentingan pribadi atau paling banter untuk kepentingan kelompok dan golongan masing masing. Ironis bukan? Dalam suasana semacam ini, semangat hijrah menjadi sangat relevan. Hijrah dalam makna yang luas dan dalam. Yaknni Hijrah dalam artian berproses transformasi menyeluruh, baik secara spiritual, sosial, maupun kultural. Hijrah bukan hanya soal pindah tempat, tetapi tentang kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik, dengan tekad, istiqamah, dan kontribusi nyata bagi diri sendiri dan lingkungan, serta sosial. Dalam konteks politik, hijrah disini bermakna proses perubahan dari politik transaksional menuju politik yang transformatif. Hijrah dari ambisi pribadi ke misi kolektif. Hijrah dari politik identitas ke politik gagasan. Dan tentu saja, hijrah dari politik kotor menuju politik bermartabat. Moralitas: Kompas Kepemimpinan Dalam Alquran, pemimpin itu digambarkan sebagai orang yang bisa dipercaya (al-amin), punya integritas, dan adil. Sifat-sifat itu bukan sekadar etika individu, tapi syarat mutlak dalam kepemimpinan publik. Seorang pemimpin yang bermoral tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai ladang mencari keuntungan, tapi sebagai ladang pengabdian. Ia akan memandang rakyat bukan sebagai komditi meraup suara angka di TPS, melainkan sebagai manusia yang harus didengar, dilayani, dan diperjuangkan haknya. Maka, mari kita renungkan. Sudahkah calon-calon pemimpin kita hari ini memiliki niat yang jernih dan mesujud dalam setiap kebijakannya? Kalaupun sudah, seberapa besar persentasenya? Sudahkah mereka siap untuk berhijrah dari pola pikir kekuasaan ke pola pikir pelayanan? Jangan-jangan, hanya soal bagaimana menang, bukan bagaimana membangun. Sebagai pemilih, kita juga harus ikut berhijrah. Berhijrah dari apatisme ke partisipasi. Berhijrah dari memilih berdasarkan “siapa yang bagi sembako” ke “siapa yang punya gagasan dan rekam jejak”. Jangan sampai semangat hijrah hanya berhenti di mimbar-mimbar pengajian, tapi tidak menembus bilik suara. Sebagai penyelenggara pemilu, saya berkomitmen memulai dari diri pribadi dan lingkungan di sekitar saya untuk tetap dan terus menjaga semangat hijrah. Dengan memaknai hijrah sebagai upaya menjaga integritas dan profesionalisme. Menjaga agar demokrasi tidak dicederai oleh kecurangan dan manipulasi. Memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua peserta. Karena pemilu yang bersih adalah fondasi utama bagi lahirnya kepemimpinan yang bermoral. Hijrah tidak bisa hanya dimaknai secara simbolik. Ia adalah gerakan perubahan. Dari keterpurukan menuju perbaikan. Dari gelap menuju terang. Dari kebohongan menuju kebenaran. Dalam politik, ini berarti komitmen untuk memperbaiki sistem, membangun kepercayaan publik, dan menempatkan etika sebagai fondasi utama pengambilan keputusan. Bayangkan jika seluruh pemimpin di negeri ini benar-benar menghidupi semangat hijrah. Tidak lagi “menyembah” kekuasaan, tapi melayani kebaikan. Tidak lagi mempertajam polarisasi, tapi merajut persatuan. Maka politik bukan lagi sesuatu yang kotor, tapi menjadi jalan mulia untuk membangun masa depan bangsa. Dan hal itu akan menjadi investasi jangka Panjang, untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Tahun Baru Islam bukan sekadar seremoni. Ini adalah undangan untuk merenung dan berubah. Hijrah bukan nostalgia sejarah, tapi ajakan untuk terus bergerak menuju kebaikan. Dalam konteks politik dan kepemimpinan, hijrah adalah ajakan untuk memaknai kekuasaan sebagai amanah, bukan kesempatan. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mau berhijrah: dari sekadar pencitraan ke keteladanan, dari retorika ke etika, dari dominasi ke kolaborasi. Mari kita sambut 1447 Hijriah dengan tekad untuk menghidupkan kembali politik yang bermoral, kepemimpinan yang jujur, dan demokrasi yang sehat. Akhirnya, selamat merayakan tahun baru Islam 1447 H. Semoga semangat hijrah Rasulullah SAW menjadi suluh bagi perjalanan bangsa ini. Dimulai dari diri pribadi, semoga berdampak pada lingkungan sosial kita.

Rasanya mafhum bagi bangsa Indonesia setiap 21 April merupakan hari Kartini. Sebagai bentuk mengenang salah satu sosok wantia yang memperjuangkan hak perempuan. Ia tidak hanya seorang perempuan yang menulis surat-surat panjang penuh gelora pikir, tetapi juga penanda zaman—sebuah simbol tentang bagaimana suara perempuan tak selayaknya dibungkam oleh batas dan kebiasaan. Bagi saya, mengenang Kartini bukan perkara seremonial. Ini adalah soal refleksi. Utamanya sebagai bagian dari penyelenggara demokrasi di tingkat lokal. Dalam kerja-kerja kepemiluan, saya menyaksikan langsung bagaimana ruang-ruang publik masih belum sepenuhnya ramah bagi perempuan, meski berbagai regulasi telah memberi jalan. Representasi politik perempuan sering kali masih menjadi angka statistik yang dikejar, bukan kesadaran yang sungguh-sungguh dihidupi. Padahal, demokrasi yang sehat harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Perempuan bukan hanya pemilih, mereka adalah pembentuk arah. Dalam setiap rumah, dalam komunitas, dan mestinya—dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Saya teringat bagaimana tulisan korespondensi Kartini kepada kurang lebih 106 sahabat penanya. Di kemudian hari disusun oleh salah satu sahabat penanya, Jascque Abendanon. Dikenal dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Bahwa Kartini menulis tentang “gelap pekat” kehidupan kaum perempuan yang perlahan-lahan harus dilawan dengan cahaya ilmu, pendidikan, dan keberanian. Emansipasi, bagi Kartini, bukan tentang menyerupai laki-laki, tetapi tentang menyadari potensi dirinya sebagai manusia yang utuh, bebas, dan merdeka. Kini, lebih dari seabad setelah Kartini berpulang, kita masih menghadapi tantangan yang tak sederhana. Perempuan yang hendak tampil sebagai pemimpin sering harus melipatgandakan usahanya. Ia harus tampil cakap, tangguh, dan tetap dianggap “diterima” dalam konstruksi sosial yang masih bias. Tidak sedikit pula yang tersandera oleh beban ganda—antara harapan publik dan urusan domestik yang belum terbagi adil. Namun harapan haruslah tetap tumbuh dan dikawal. Di Balikpapan, saya melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam kerja-kerja pemilu—sebagai penyelenggara, pengawas, relawan, hingga penggerak komunitas. Mereka hadir dengan dedikasi, integritas, dan kepekaan yang menjadi nilai tambah bagi demokrasi kita. Beberapa dari mereka bahkan menjadi pemimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam struktur adhoc penyelenggara pemilu. Ada yang memimpin logistik, mengelola perencanaan, hingga menjadi juru bicara yang mampu menjembatani pemilih dengan informasi yang mencerahkan. Mereka tidak hanya bekerja dengan sistem, tetapi dengan hati. Kita juga tidak boleh melupakan tokoh-tokoh perempuan di Kalimantan Timur yang selama ini menjadi pionir dalam pembangunan sosial dan politik. Baik di DPRD, dalam organisasi masyarakat, maupun sebagai tokoh adat dan budaya. Keteladanan mereka membuktikan bahwa kepemimpinan tidak mengenal jenis kelamin—ia adalah soal visi dan keberanian mengambil tanggung jawab. Tugas kita bersama hari ini adalah merawat ruang ini. Membuka kesempatan lebih luas, mendorong afirmasi yang sehat, dan mendidik publik untuk menilai kepemimpinan bukan dari jenis kelamin, melainkan dari kapasitas, rekam jejak, dan komitmen. Sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, saya meyakini bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan adalah bagian dari ajaran luhur yang diwariskan para guru kami. Dan Kartini, dalam versinya sendiri, telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu bisa diperjuangkan lewat tulisan, keberanian, dan ketulusan. Kartini mengawali perjuangan ini dengan pena. Kini, sepatutnya kita melanjutkannya dengan kebijakan, kebudayaan, dan keberanian untuk mengubah cara pandang. Sebab demokrasi sejati bukan hanya tentang suara yang dihitung, tapi tentang siapa yang benar-benar diberi ruang untuk bersuara. Prakoso Yudho Lelono

Penulis: Prakoso Yudho Lelono, S.H.I Ketua KPU Kota Balikpapan SETIAP tahun, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai penghormatan pada semangat yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua memperingati Hardiknas dengan sudut pandang reflektif. Sebagai wujud semangat, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Setiap peringatan Hardiknas menyimpan rasa hormat pada semangat yang diusung. Tapi di sisi lain, sebagai bentuk pemikiran yang reflektif, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama: sudahkah pendidikan kita hari ini benar-benar memerdekakan? Sebagai penyelenggara pemilu di Kota Balikpapan, saya memang bukan guru, bukan kepala sekolah, apalagi pakar pendidikan. Tapi saya percaya, kerja-kerja demokrasi yang saya jalani sehari-hari sampai hari ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan bangsa ini. Demokrasi yang sehat hanya mungkin tumbuh dari rakyat yang berpengetahuan, beretika, dan memiliki nalar kritis. Itu semua dibentuk dari proses pendidikan, sejak dini. Pendidikan Politik Sejak Dini Saya berkeyakinan bahwa pendidikan adalah akar dari semua proses demokrasi. Di ruang kelas, anak-anak belajar tentang nilai, tanggung jawab, dan kebersamaan. Kalau nilai-nilai itu kuat sejak kecil, mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang sadar dan peduli. Mereka tidak akan mudah diseret oleh politik uang, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, apalagi apatis terhadap proses politik. Karena pemahaman dan kesadaran terhadap proses politik telah ditanamkan sejak dini. Sebaliknya, jika ruang-ruang pendidikan justru membentuk sikap pasif, asal ikut-ikutan, atau bahkan membenarkan praktik curang, maka kita sedang menanam benih krisis demokrasi. Pilkada Balikpapan 2024 yang baru saja kita lewati memberi banyak pelajaran. Kami di KPU Kota Balikpapan telah berusaha membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, tetapi semua itu tidak akan berarti jika masyarakat kita belum punya kesadaran kritis untuk ikut menjaga prosesnya. Dan kesadaran itu hanya mungkin lahir dari pendidikan yang membebaskan. Pendidikan politik sejak dini merupakan suatu keniscayaan, dan harus kita kawal bersama. Saya percaya hal ini telah berlangsung, tetapi perlu kita tingkatkan bersama. Untuk itu saya sering membayangkan: bagaimana jika sejak SMP atau SMA, anak-anak diajak untuk berdiskusi tentang perbedaan pandangan politik, belajar tentang proses pemilu, bahkan dilatih untuk menjadi pemimpin dalam organisasi sekolah? Bukan untuk membuat mereka “dewasa sebelum waktunya”, tetapi agar mereka paham bahwa politik bukan melulu soal praktik taktik mencapai tujuan dengan cara yang kotor. Melainkan ada sudut pandang positif lainnya yang perlu mereka ketahui: bahwa proses politik akan menghasilkan kebijakan yang menentukan nasib suatu masyarakat. Pendek kata, semua aktivitas masyarakat tidak terlepas dari kebijakan politik. Terlalu lama kita memisahkan pendidikan dari kehidupan publik. Padahal, pendidikan yang baik harus mampu membentuk manusia yang berpikir, beretika, dan berani mengambil peran. Pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak sarjana, tapi juga membentuk warga negara yang sadar. Pendidikan, Antara Idealitas dan Realitas Saya pribadi sangat setuju dan menyambut baik semangat Merdeka Belajar. Gagasan itu punya ruh yang kuat: bahwa setiap anak punya cara belajar masing-masing, dan pendidikan harus memberi ruang bagi keberagaman. Tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Tak jarang ditemui banyak guru yang belum dibekali pelatihan cukup. Sekolah-sekolah di daerah pelosok negeri ini kesulitan menyesuaikan kurikulum. Dan sering kali, kita masih terjebak dalam angka-angka: nilai, peringkat, akreditasi—hal-hal yang kadang mengaburkan tujuan sejati pendidikan itu sendiri. Jika kita ingin pendidikan yang benar-benar memerdekakan, maka kita harus berani beranjak dari paradigma lama. Pendidikan bukan pabrik ijazah. Ia adalah proses panjang membentuk manusia seutuhnya. Di era globalisasi saat ini, pendidikan karakter menjadi sangat relevan dan mendesak. Dunia kerja dan masyarakat menuntut lebih dari sekadar kecakapan akademik; integritas, empati, kerja sama, dan ketahanan mental menjadi kualitas yang sangat dibutuhkan. Pendidikan karakter membantu peserta didik mengenali dan membentuk nilai-nilai dasar yang akan mereka pegang seumur hidup. Di tengah gempuran informasi digital, banjir opini di media sosial, dan tekanan hidup yang semakin kompleks, karakter yang kuat menjadi jangkar yang menjaga seseorang tetap berpijak. Maka, pendidikan kita harus berani meletakkan karakter sebagai fondasi utama, bukan pelengkap semata. Balikpapan dan Masa Depan Pendidikan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) punya tantangan besar. Pembangunan fisik di kota ini begitu pesat. Tapi, apakah kita sudah seimbang membangun manusianya? Kota ini tidak boleh hanya punya jalan tol dan pelabuhan megah. Kota ini harus punya sekolah yang inklusif, guru-guru yang sejahtera, dan ruang belajar yang ramah bagi semua anak. Pendidikan harus jadi investasi jangka panjang kita. Karena tanpa pendidikan, semua kemajuan itu akan kosong. Sebagai penyelenggara pemilu, saya berharap pemilu dan semua penyelenggaraan suksesi kepemimpinan ke depan diikuti oleh generasi yang lebih melek informasi, lebih kritis, dan lebih peduli. Dan itu harus terus kita gaungkan dari ruang-ruang pendidikan kita. Saya bukan hendak menggurui. Saya hanya ingin mengajak kita semua—orang tua, guru, pejabat berwenang, warga biasa (kita semua)—untuk turut serta merefleksikan kembali arah pendidikan kita. Apakah ia benar-benar membebaskan, atau justru makin menekan? Apakah ia menguatkan masyarakat, atau justru menciptakan ketimpangan baru? Hari Pendidikan Nasional tidak cukup hanya diperingati dengan upacara atau kata-kata indah. Ia harus jadi waktu untuk menengok ke dalam dan bertanya: sudah sejauh mana kita memberi kesempatan yang adil bagi setiap anak bangsa untuk tumbuh dan belajar? Semoga kita tidak lelah memperjuangkan pendidikan yang berpihak pada semua. Pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan, tapi juga manusia-manusia yang berani berpikir, jujur bertindak, dan siap membangun bangsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025.

Oleh : Syahrul Karim Anggota KPU Kota Balikpapan 2019-2024 Sekitar lima bulan lagi tepatnya 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum lima kotak suara. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Sejak pemilihan umum dilaksanakan secara langsung tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih tidak lagi diatas angka 90 persen seperti pada raihan pemilu sebelumnya, rezim orde baru dan pemilu pasca reformasi di tahun 1999. Berdasarkan data KPU RI, partisipasi pemilih tahun 2004 sebesar 84,7 persen, tahun 2009 turun menjadi 71 persen, selanjutnya pemilu tahun 2014 kembali naik menjadi 75,11 persen dan pemilu terakhir 2019 naik diangka 81,69 persen meskipun pelaksanaanya ditengah bencana Covid 19. Pasca pemilu tahun 2014 dan setelah ditetapkan UU/7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilakukan secara bersamaan yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih anggota legislatif. Hal yang sama juga diterapkan pada pemilu 2024. Dalam tulisan ini penulis ingin mengajak masyarakat melihat lebih jauh tingkat kualitas pemilih dalam menggunakan hak politiknya pada pemilu tahun 2019 dan bagaimana kualitas pemilih pada pemilu 2024. Salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sejak dimulainya hingga selesainya tahapan pemilu. KPU secara kelembagaan yang melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemilu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara menyadari, bahwa perlu dukungan dan partisipasi tiap Warga Negara ikut ambil bagian dalam seluruh pelaksanaan tahapan pemilu terutama penggunaan hak politiknya pada hari pemungutan suara. Ini didukung dengan terbitnya PKPU 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dimana menekankan pada hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Hak tersebut adalah diseminasi informasi Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Namun wajib menjujung tinggi prinsip netralitas atau non partisan seperti melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar dan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu. Jamak diketahui bahwa ukuran kesuksesan pemilihan umum selalu didasarkan pada angka matematis-tingkat partisipasi. Yakni warga yang sudah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya atau mencoblos di hari pemungutan suara. Namun jika dikaitkan dengan kualitas pemilih dalam konteks penggunaan surat suara maka kita bisa melihat lebih jauh data hasil pemilu tahun 2019 pada surat suara tidak sah pemilih. Data KPU Kota Balikpapan menunjukan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk seluruh tingkatan pemilihan, dimana surat suara Presiden dan Wakil Presiden paling rendah surat suara tidak sah, hanya 1,9 persen dari jumlah keseluruan pemilih. Berbeda halnya dengan pemilihan anggota legislatif. Surat suara DPD paling tinggi tidak sahnya diantara surat suara legislatif lainnya. Mencapai 19 persen. Selanjutnya surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi hampir sama 17 persen. Sedangkan surat suara tidak sah paling rendah adalah DPRD Kota sebesar 7 persen. Kondisi ini menunjukan ada banyak pemilih datang ke TPS hanya untuk mencoblos beberapa surat suara kendati diberikan lima surat suara oleh petugas KPPS. Kecuali pemilih yang tidak masuk dalam kategori lima surat suara seperti kategori pindah memilih (DPTb) dengan alasan tertentu yang diatur dalam PKPU 7/2022. Diantaranya menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, tugas belajar dan pindah domisili. Surat suara yang tidak coblos tersebut secara langsung dinyatakan invalid atau tidak sah pada saat dilakukan penghitungan. Hal ini membuktikan pemilihan calon anggota legislatif kalah pamor dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Faktor paling utama adalah penyuguhan informasi secara massif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tidak pungkiri hampir seluruh ruang media, baik ranah digital ataupun media massa, lebih banyak disajikan informasi paslon Pilpres. Sementara pemberitaan pemilihan anggota legislative sangat minim terutama pada caleg DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi bahkan DPRD Kab/Kota. Tidak lain karena paslon Presiden dan Wakil Presiden hanya hitungan jari. Minimal dua paslon. Sehingga masyarakat sangat mudah mengenali paslon Presiden dan wakilnya. Dan juga Presiden merupakan jabatan nomor wahid dengan kekuasaan besar dimilikinya yang menjadikannya isu strategis oleh media mainstream hingga menghiasi media sosial. Sementara, terdapat banyak sekali calon anggota legislatif dari berbagai partai politik. Misalnya saja di Balikpapan ada sekitar 650 bacaleg dari 17 parpol memperebutkan 45 kursi di DPRD Kota. Dibutuhkan waktu banyak untuk mencari tahu profile seluruh caleg tersebut. Sama Pentingnya Pilpres dan Pileg Masyarakat harusnya memahami, penyelenggaraan pemilu Presiden dan legislatif adalah sama pentingnya. Pilpres untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan menangani masalah pemerintahan, Pileg untuk memilih wakil rakyat yang menangani persoalan di legislatif yaitu membuat regulasi, kebijakan anggaran dan fungsi pengawasan. Regulasi menjadi dasar aturan hukum dalam tata kelolah pemerintahan bernegara. Pemahaman lainya, Pemilu merupakan saluran yang menghubungkan publik ke pemerintahan. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam kerangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah, kebijakan dan program yang dihasilkannya. Dengan Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Wakil-wakil itu menjadi penyambung kepentingan rakyat atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Alasan lainya, pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat yang bersifat langsung, dan terbuka. Diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Peran itu terutama wajib dilakukan oleh partai politik peserta pemiluh berserta individuindividunnya (baca: caleg). Penyajian materi peserta pemilu harusnya bersifat konstruktif seperti ideologi, program dan kebijakan sebagai bahan evaluasi pemilih menentukan pilihannya secara tepat agar kelak terpilih anggota legislatif yang mempunyai kapasitas, integritas dan kompetensi. Bukan sebaliknya untuk meraih suara pemilih menggunakan tindakan dengan cara cara inkonstitusional dan amoral yang hanya merusak tatanan demokrasi. Politik uang dan politik identitas. Tentunya dalam mewujudkan Pemilu berkualitas harus melibatkan partisipasi secara meluas guna membentuk pemahaman atau literasi politik yang memadai. Sehingga tujuan dilaksanakan Pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural semata, namun yang lebih substansi menjadikan partisipasi dan dukungan rakyat sebagai mandat memperjuangkan aspirasi, visi, dan misi yang menjadikan harapan dan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dapat tercapai. Oleh karenanya, peran serta masyarakat, peserta pemilu, Perguruan Tinggi, CSO (masyarakat sipil) terutama media massa, dapat memberikan porsi yang sama dalam menyajikan informasi pemilu. Tidak terbatas pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Harapannya, kesuksesan pemilu 2024 tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS, tapi juga menjadikan pemilu berkualitas dengan instrument rendahnya surat suara tidak sah terutama pada Pileg. Jika hal ini dapat dilakukan maka kualitas pemilu 2024 baik Pilpres maupun Pileg semakin baik dibanding dengan pemilu 2019. Kendati pilihan pemilih dalam bilik suara tetap menjadi hak politik pemilih yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk golput sekalipun.